STARJOGJA.COM, OPINI – Sepakbola Indonesia memang identik dengan suporter fanatik. Di Jakarta ada Jakmania, Malang dengan Aremania, Surabaya dengan Bonek, Makassar punya Maczman, bahkan di Jogja ada dua kelompok suporter fanatik, Slemania di Sleman dan Brajamusti di Kota Jogja.
Dua suporter yang terakhir disebut memiliki klub kebanggan yang sama-sama bermain di kasta kedua Liga Indonesia yakni, PSS dan PSIM. Kedua klub tersebut bukanlah klub kemarin sore. Keduanya adalah klub “dewasa” di dunia sepak bola Indonesia. PSIM berdiri sejak 1929 sedangkan PSS berdiri sejak 1976.
Mengutip pernyataan Wibawa (2014:80), konflik yang terjadi antara Slemania dan Brajamusti merupakan konflik terbuka, memiliki akar yang dalam dan sangat nyata serta memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya apalagi ini merupakan konflik yang ada sejak awal tahun 2000an.
Konflik puluhan tahun inilah yang belum membawa kedua kelompok fanatik ini pada tataran kedewasaan sebagai suporter. Puluhan tahun bertetangga, puluhan kali pula masyarakat sepak bola disuguhkan dengan berita bentrok kedua suporter, bahkan berakhir anarkis dan ada korban tewas. Terakhir, kejadian di Stadion Sultan Agung Bantul ,Kamis (26/7).
Dua jam sebelum kick off terjadi bentrokan antar kedua suporter tim tersebut. Jalan menuju stadion dipenuhi sesak para suporter. Sayangnya berakhir bentrok. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan bentrokan tersebut. Namun memang jika ada bara, maka api akan cepat tersulut. Bentrokan pun tidak terelakkan.
Aparat keamanan dibuat begitu sibuk untuk melerai kedua kelompok suporter itu. Bukan hanya di ruas jalan menuju stadion, informasi terkahir yang penulis terima saat menulis artikel ini, seorang siswa bernama Iqbal (17) asal SMKN Pleret tewas akibat di keroyok suporter di Stadion Sultan Agung. Bahkan ketika di keroyok Iqbal tidak menggunakan atribut kedua kelompok suporter. Nahas. Untuk menonton sepak bola secara damai saja harus dibayar dengan nyawa.
Tensi tinggi diantara kedua suporter memang masih tinggi, tapi apa memang tidak bisa sebagai pemain ke-12 yang mendukung klubnya masing-masing secara dewasa dan damai? Hal ini secara khusus juga dijadikan objek penelitian oleh Wibawa (2014) bahwa banyak anak dibawah umur atau remaja yang baru menjadi suporter sehingga mereka masih labil.
Disinilah diperlukan kewibawaan bagi para pengurus suporter maupun korwil untuk ikut mendewasakan dan sosialisasikan tentang damainya sebuah persaudaraan dalam dunia sepakbola. Para pengurus pun demikian adanya, bukan hanya suporter remaja saja yang menjadi perhatian tapi bagaimana menanamkan kedewasaan kepada setiap suporter itulah yang penting. Program-program seperti silaturahmi kepada kelompok suporter lain bisa jadi solusi kecil untuk masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik.
Satu lagi ancaman terbesar suporter di era digital seperti sekarang ini. Isu hoax di media sosial yang menyebar di kalangan suporter pun harus segera diminimalisir. Dari isu hoax sekecil apapun bisa menyulut konflik besar tanpa didasari fakta yang kuat. Inilah pentingnya mengkonfirmasi kepada ketua korwil maupun pengurus di kelompok suporter masing-masing jika mendapatkan isu dan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Mari bersama-sama ciptakan kondisi persepakbolaan tanah air yang damai. Jika konflik terus, dimana arti bendera fair play berwarna kuning yang dibawa setiap awal pertandingan itu?
Ingat, fair play bukan hanya ada di lapangan, tapi juga rivalitas kelompok suporter di luar lapangan. Dewasalah !!!
Penulis : Cakra Virajati – Pecinta Sepakbola Indonesia
Referensi : Wibawa, Irawan Haris. (2014). Konflik Suporter Sepakbola (Penelitian Tentang Suporter Slemania versus Brajamusti di Yogyakarta). Fisipol UGM. Yogyakarta


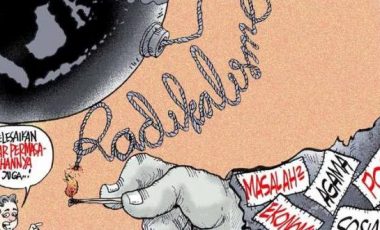




Comments